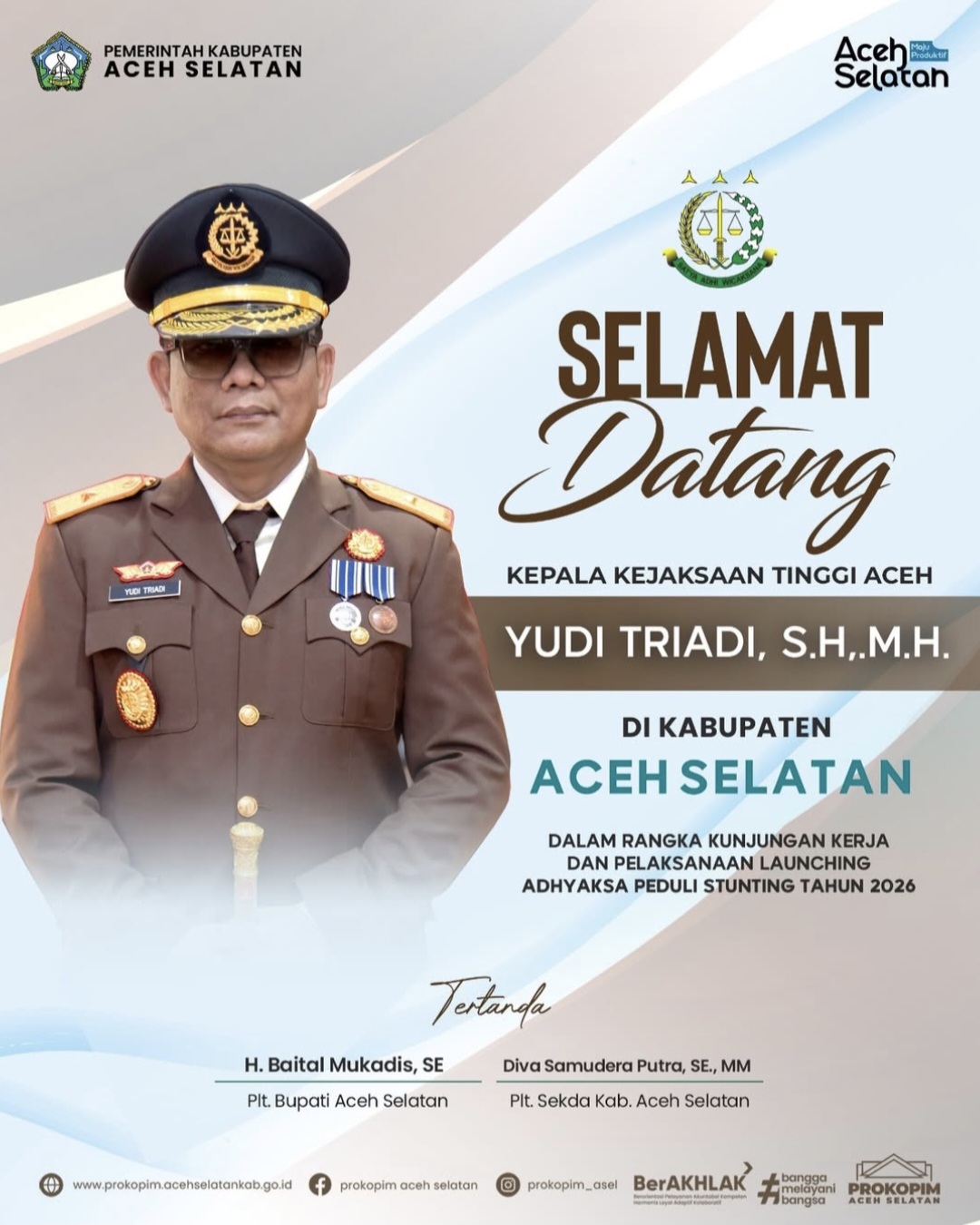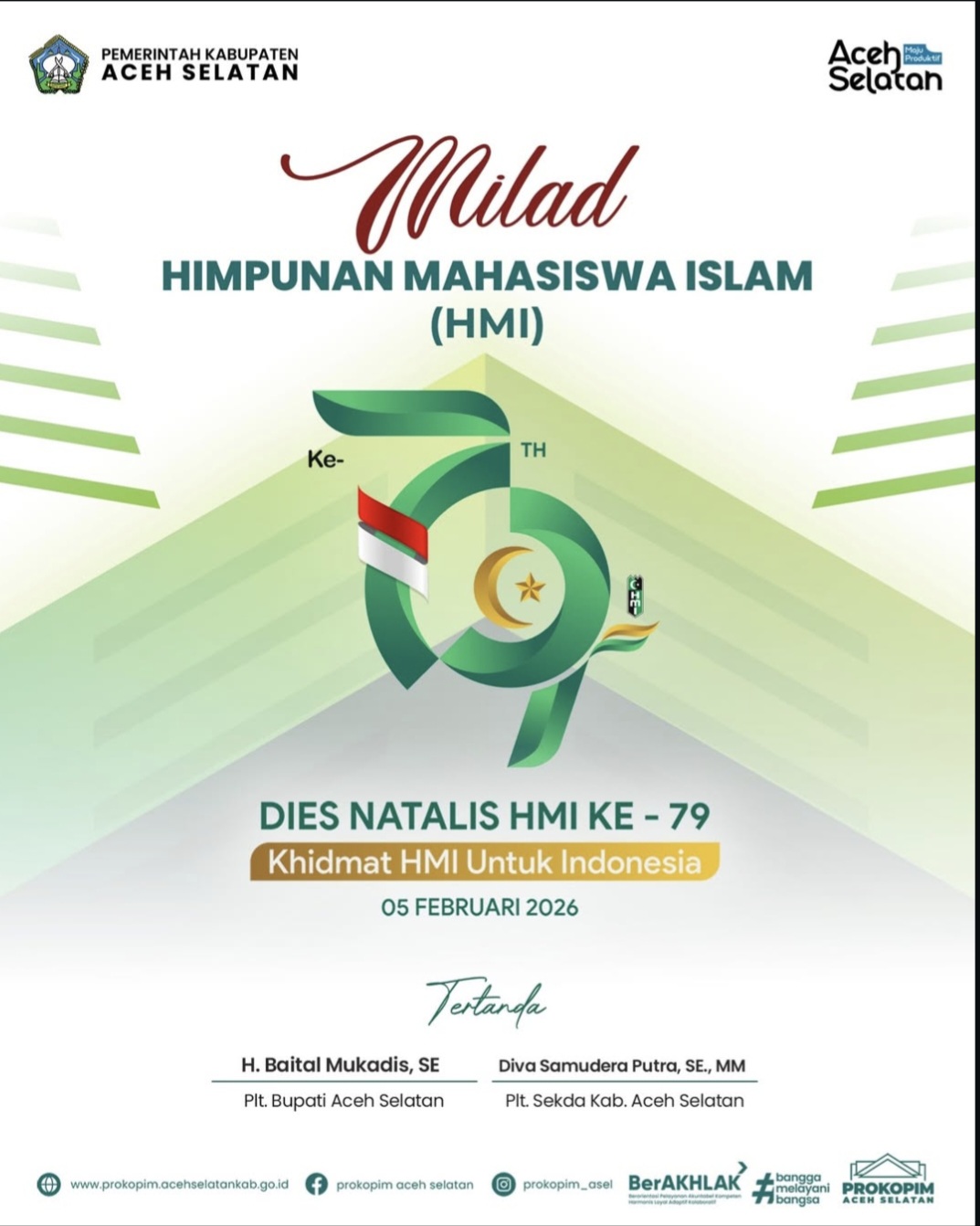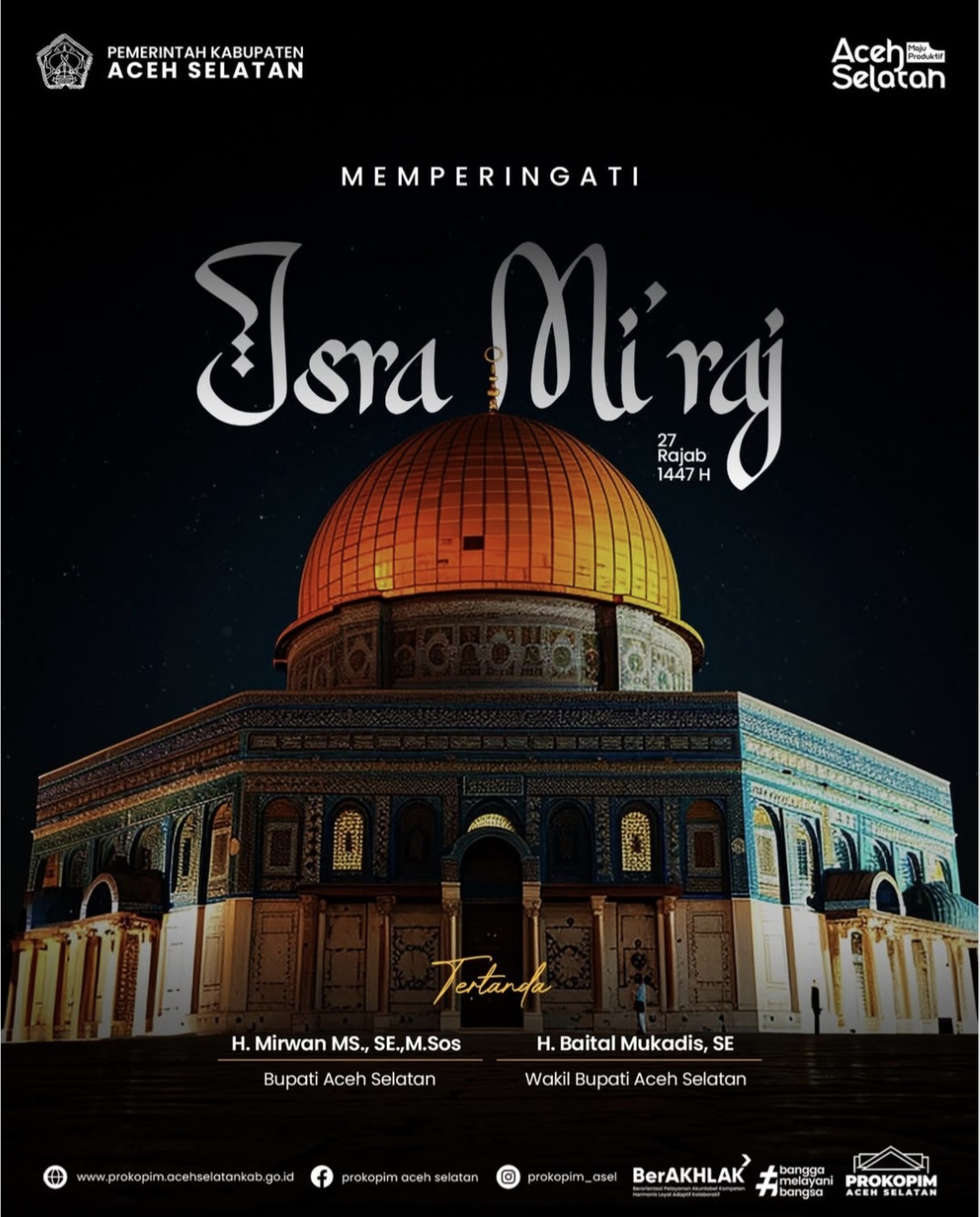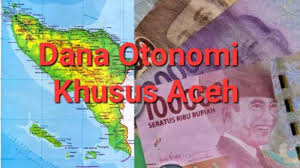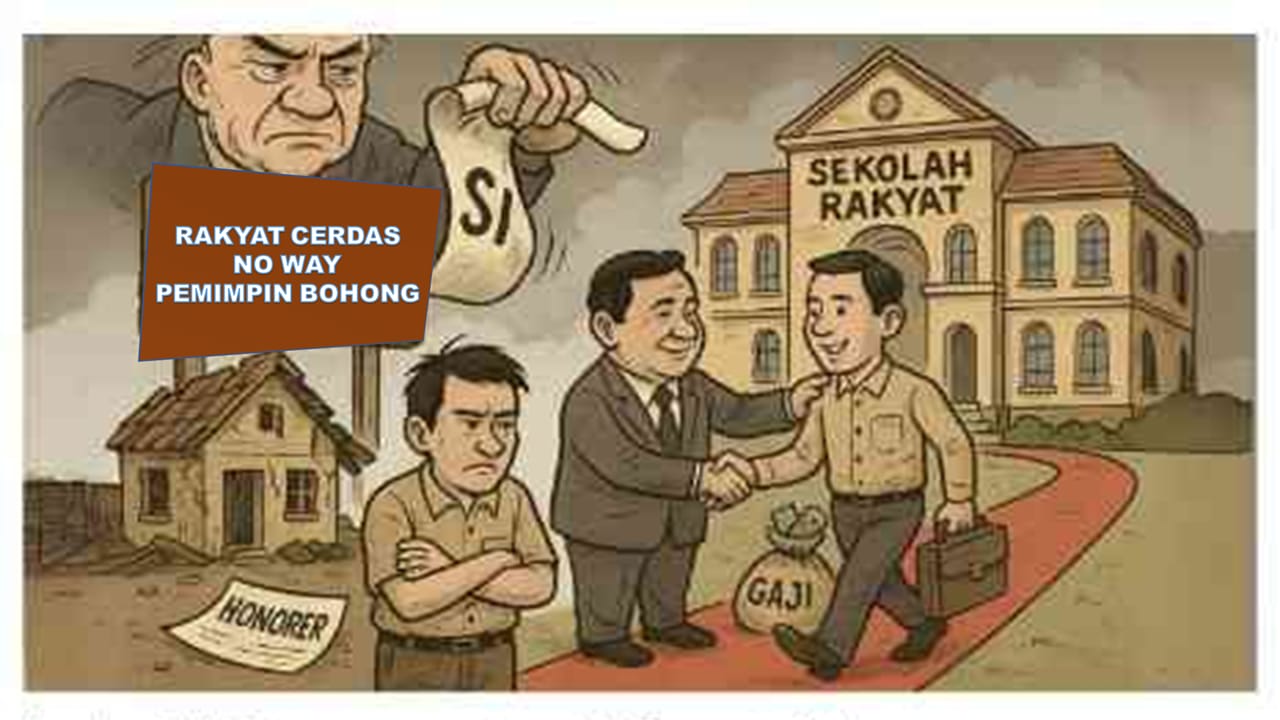Mens Rea Separatis di Gedung Parlemen Aceh
Yong - Redaksi
Rabu, 03 September 2025

Opini
282 views
Katapoint.id - Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, pada 1 September 2025 kembali membuka luka lama politik di Tanah Rencong. Di hadapan wartawan dan publik, Zulfadli menantang massa demonstran dengan kalimat provokatif“Aceh pisah dari Pusat (Indonesia). Berani tulis? Sini saya teken.” Ucapan itu, yang terdengar seperti lelucon politik, justru menyimpan bobot hukum yang serius yaitu indikasi adanya mens rea sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan.
Dalam literatur hukum pidana, mens rea menjadi unsur penting untuk menentukan ada tidaknya kesengajaan dalam suatu tindak pidana. Kalimat Zulfadhli bukan sekadar ekspresi emosional, namun diucapkan oleh pejabat publik dengan kapasitas politik, dalam forum terbuka, di tengah massa yang sedang memanas. Kombinasi ini cukup untuk menafsirkan adanya intensi yang bisa memantik tindakan destruktif. Lebih jauh, pernyataan tersebut mudah dibaca sebagai indoktrinasi ide separatisme, sesuatu yang secara tegas bertentangan dengan konstitusi dan Perjanjian Helsinki 2005 sebagai fondasi perdamaian Aceh pasca konflik.
Aceh memang punya sejarah panjang relasi tegang dengan Jakarta. Literatur politik pasca konflik, seperti kajian Edward Aspinall dan Anthony Reid, menekankan bahwa perdamaian di Aceh hanya mungkin bertahan bila elite politik lokal menjaga keseimbangan antara identitas Aceh dan komitmen kebangsaan. Pernyataan Zulfadhli justru menabrak keseimbangan rapuh itu. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik pada institusi demokrasi, ia justru menghidupkan kembali retorika lama yang seharusnya sudah terkubur bersama senjata di tahun 2005 silam.
Konsekuensinya tidak ringan. Pertama, dari sisi hukum, pernyataan ini bisa dijerat pasal-pasal KUHP tentang makar atau upaya memisahkan diri dari negara. Yurisprudensi menunjukkan, ucapan publik yang mendorong disintegrasi dapat dikualifikasikan sebagai delik formil, di mana niat saja sudah cukup untuk menimbulkan konsekuensi pidana. Kedua, dari sisi politik, ucapannya menyeret Partai Aceh ke dalam pusaran polemik nasional. Mualem, sebagai Ketua Umum, kini dipaksa memberi klarifikasi agar pernyataan tersebut tidak menjadi bola liar yang dieksploitasi kelompok yang menghendaki instabilitas.
Namun, ada fakta lain yang patut dicatat. Aksi unjuk rasa 1 September di Banda Aceh berlangsung relatif damai. Rakyat Aceh tetap menjunjung tinggi hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat tanpa terjerumus dalam kekerasan. Ini menandakan bahwa masyarakat sudah matang secara politik, mampu mengelola perbedaan tanpa mengulang pola konflik bersenjata masa lalu. Perdamaian Aceh, dengan segala dinamika dan problem implementasinya, adalah simbol kebesaran jiwa rakyat Aceh untuk menjaga amanah sebuah perjanjian.
Di titik inilah ucapan Zulfadhli terasa semakin kontra produktif. Di tengah meningkatnya tensi politik nasional akibat gelombang demonstrasi, justru diperlukan sikap kenegarawanan dari elite Aceh, bukan provokasi bernuansa separatis. Seorang ketua parlemen daerah semestinya menjadi jangkar demokrasi, bukan corong agitasi. Bila dibiarkan, pernyataan seperti ini bisa menurunkan derajat politik Aceh dari teladan perdamaian menjadi ancaman instabilitas.
Pemerintah pusat dan aparat penegak hukum sebaiknya menanggapi pernyataan ini secara proporsional, dengan tetap menghormati kebebasan berekspresi namun tidak kompromi terhadap ujaran bernuansa separatis yang dilakukan pejabat publik. Dalam demokrasi, kritik boleh keras, tapi ancaman disintegrasi tidak bisa dinegosiasikan. Aceh telah membayar harga mahal untuk kedamaian. Sudah selayaknya semua pihak, terutama elite politik, menjaga warisan itu dengan bijak, bukan dengan retorika yang membuka kembali pintu konflik.[]
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Komentar
Baca juga